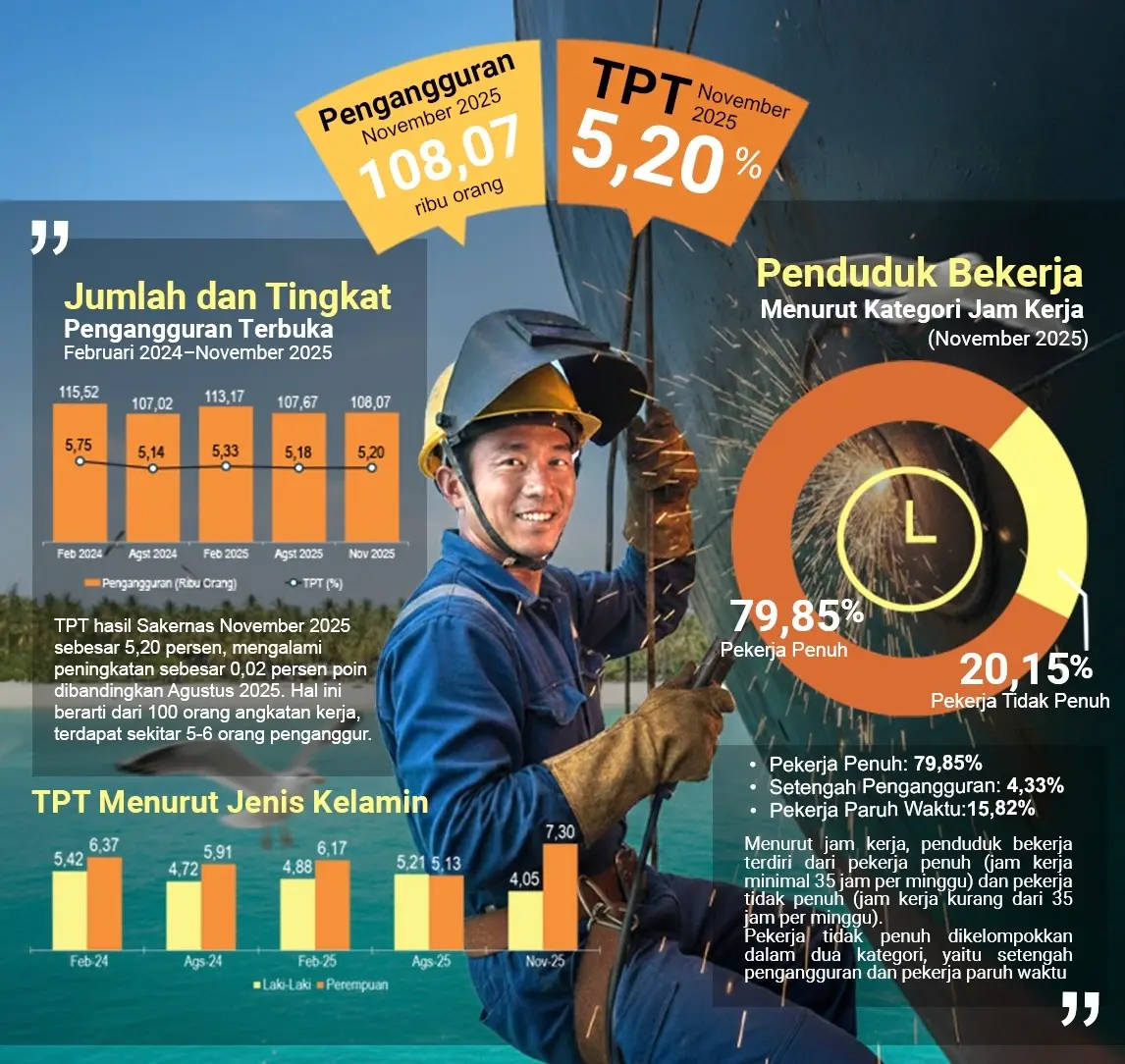KALTIM VOICE, BALIKPAPAN – Tren kerja fleksibel yang meningkat tajam sejak pandemi COVID-19 membawa tantangan baru dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Meski menawarkan efisiensi dan fleksibilitas bagi pekerja, sistem kerja fleksibel atau flexible working arrangement masih belum sepenuhnya terlindungi oleh hukum yang berlaku. Hal ini menjadi sorotan penting dalam kajian hukum terbaru yang ditulis oleh Wahyuni Nur Fitriah, SH., MH., seorang akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balikpapan.
Dalam kajiannya, Wahyuni menegaskan bahwa kerja fleksibel telah menjadi keniscayaan di era digital, namun belum diikuti oleh regulasi hukum yang mampu menjamin hak-hak pekerja secara adil. “Negara perlu memastikan bahwa fleksibilitas bagi pengusaha tidak berubah menjadi ketidakpastian bagi pekerja,” ujarnya.
Model kerja fleksibel mencakup berbagai bentuk, seperti kerja jarak jauh (remote working), kerja paruh waktu, sistem kontrak proyek, hingga pekerjaan berbasis platform digital seperti Gojek dan Upwork. Sistem ini memang memungkinkan efisiensi serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional, terutama bagi generasi muda dan perempuan.
Namun, model kerja ini juga berisiko tinggi terhadap pelemahan posisi pekerja, terutama karena banyaknya bentuk kerja fleksibel yang berada di luar jangkauan perlindungan hukum formal. Banyak pekerja tidak memiliki kontrak kerja tertulis, tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak menerima hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Secara konstitusional, UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) telah menjamin hak atas pekerjaan dan perlakuan adil dalam hubungan kerja. Namun dalam praktiknya, menurut Wahyuni, regulasi nasional seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) belum cukup responsif terhadap realitas kerja fleksibel yang semakin berkembang.
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 serta beberapa surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan memang telah memberikan dasar perlindungan, terutama bagi pekerja kontrak dan outsourcing. Akan tetapi, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur kerja berbasis platform digital atau gig economy.
“Fleksibilitas bagi pemberi kerja bisa berarti ketidakpastian bagi pekerja,” tulis Wahyuni, menggarisbawahi potensi eksploitasi terselubung dalam sistem kerja baru ini.
Dalam aspek penegakan hukum, pekerja fleksibel masih bisa menuntut haknya melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. UU No. 2 Tahun 2004 menyebut bahwa hubungan kerja tidak selalu harus berbentuk kontrak tertulis, melainkan dapat dibuktikan melalui unsur perintah, upah, dan pekerjaan.
Namun dalam praktiknya, banyak pekerja yang tidak mengetahui hak tersebut atau enggan melaporkan karena posisi tawar yang lemah.
Wahyuni menekankan pentingnya reformasi regulasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Negara, menurutnya, harus segera mengakui bentuk kerja berbasis platform digital sebagai bagian dari hubungan kerja resmi. Selain itu, diperlukan pula perlindungan terhadap jaminan sosial, keselamatan kerja, dan diskriminasi digital.
“Kerja fleksibel adalah keniscayaan di era digital, namun hukum tidak boleh kehilangan peran sebagai pelindung bagi pihak yang lemah dalam hubungan industrial,” tegasnya.
Transformasi dunia kerja ke arah yang lebih fleksibel memang tidak dapat dihindari. Namun, adaptasi hukum perlu dilakukan secara cepat dan tepat agar prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap tenaga kerja tetap menjadi prioritas utama dalam setiap perubahan. (Mzhra).